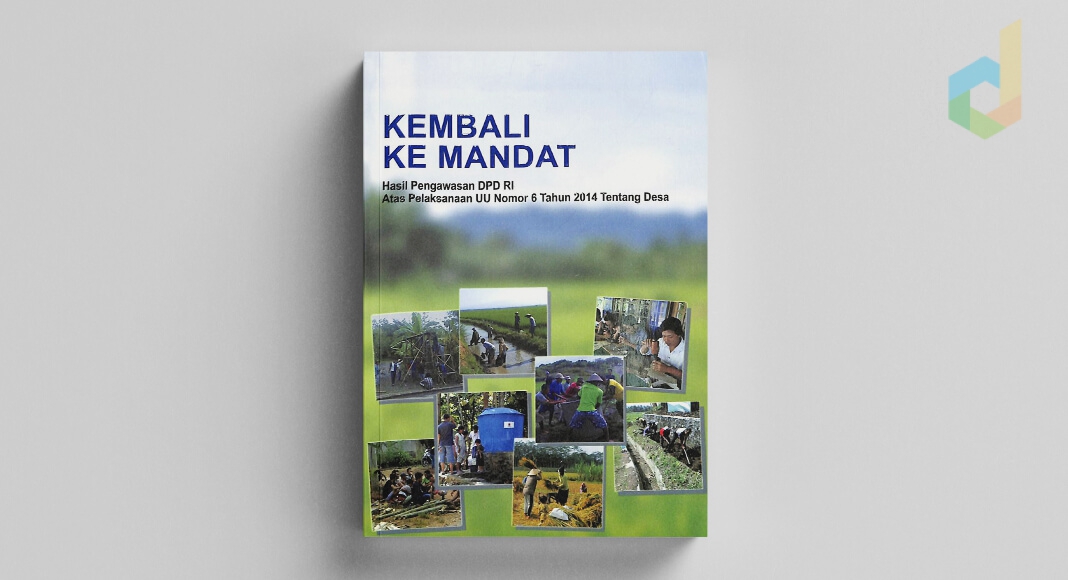“Kami harus menghancurkan desa dengan tujuan untuk menyelamatkannya,” demikian ungkap tentara Amerika ketika melakukan serangan terhadap desa-desa di Vietnam (New York Times, 8 February 1968).
Serangan itu dilakukan untuk menghancurkan komunisme yang bersarang di desa. Dalam era dekolonisasi dan Perang Dingin, persaingan, transformasi desa menjadi terkait erat dengan proyek-proyek pembentukan negara, hegemoni global, dan pelestarian kekaisaran.
Para pemimpin Barat dan ahli pembangunan memandang desa di Asia penuh dengan bahaya, yang menciptakan ketakutan akan disorder, sebab desa merupakan tempat bernaung kaum petani yang kacau, basis feodalisme, bahkan rumah bagi komunisme.
Negara, selain gencar masuk ke desa dengan pembangunan, juga melakukan depolitisasi dan deparpolisasi untuk memotong pertautan politik antara partai politik dengan rakyat desa, akibat trauma dengan Parpol sebelumnya. Pada awal Orde Baru banyak kepala desa di Jawa diisi PJS dari tentara.
Pada tahun 1969 pemerintah mengeluarkan UU No. 6/1969 yang dimaksudkan untuk membekukan UU sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 tahun 1961 tentang Pembuatan Perjanjian Persahabatan Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok, dan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang baik yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar maupun yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi.
Lima tahun kemudian pemerintah mengeluarkan UU No. 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah yang betul-betul merupakan versi Orde Baru, yakni UU itu merupakan instrumen untuk memperkuat birokratisasi, otoritarianisme, sentralisasi dan pembangunan.
UU itu bukanlah kebijakan yang berorientasi pada desentralisasi untuk memperkuat otonomi daerah atau membentuk pemerintahan daerah (local government), melainkan berorientasi pada pembentukan pemerintahan pusat yang bekerja di daerah (the local state government).
Ini bisa dilihat begitu kuatnya skema dekonsentrasi (desentralisasi administratif) ketimbang devolusi (desentralisasi politik) dalam UU No. 5/1974.
Lima tahun berikutnya, Pemerintah mengeluarkan UU No. 5/1979 tentang pemerintahan desa. Sebegitu jauh UU No. 5/1979 mengabaikan spirit keistimewaan dan keragaman kesatuan masyarakat lokal yang tertuang dalam Pasal 18 UUD 1945, seraya membuat format pemerintahan desa secara seragam di seluruh Indonesia.
UU ini menegaskan: “Desa adalah wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai persatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri”.
Ketika UU ini masih berstatus RUU, pemerintah berpendapat: “bahwa desa dimaksudkan sebagaimana dimaksudkan dalam RUU ini, bukanlah merupakan salah bentuk daripada Pembagian Daerah Indonesia Atas Daerah besar dan kecil sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 18 UUD 1945.
Masalah pembagian daerah Indonesia atas Daerah besar dan kecil itu kiranya sudah cukup diatur dengan UU No.5/1974. Pengertian daerah besar adalah wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan seterusnya, sehingga oleh karenanya sukar untuk diartikan, bahwa daerah yang lebih kecil itu juga mencakup desa sebagaimana dimaksud dalam RUU ini.”
Dari ketentuan awal, termasuk pengertian desa yang seragam itu, UU No. 5/1979 secara menyolok menghendaki modernisasi dan birokratisasi pemerintahan desa, negaranisasi (negara masuk ke desa) dan marginalisasi terhadap keragaman kesatuan masyarakat hukum adat. Banyak pihak menilai bahwa UU No. 5/1979 merupakan bentuk Jawanisasi atau menerapkan model desa Jawa untuk kesatuan masyarakat adat di Luar Jawa. Dengan sendirinya UU ini tidak mengakui lagi keberadaan Nagari, Huta, Sosor, Marga, Negeri, Binua, Lembang, Parangiu dan lain-lain yang umumnya berada di Luar Jawa.
Prof. Selo Soemardjan, Bapak Sosiologi Indonesia, memberikan catatan panjang terhadap UU No. 5/1979 itu:
Meski bernama UU tentang Pemerintahan Desa, namun UU No 5/1979 tidak memberi otonomi kepada desa, juga tidak menyatakan desa adalah daerah administratif, berbeda dengan kelurahan dalam kotamadya yang dinyatakan daerah administratif.
Lalu, bagaimana status desa? Otonomi tidak, administratif juga tidak. Bahkan pemerintah desa yang lama berakar kuat dalam adat, dipisahkan dari adat.
Pemisahan menurut hukum adat dan pemerintahan desa yang semula bersatu itu, membawa konsekuensi jauh.
Dengan pemisahan itu, pemerintah desa berkewajiban lebih besar melayani pemerintah, proyek dan program yang datang dari atas.
Bila hal-hal itu bertentangan dengan adat yang pada dasarnya melindungi kepentingan masyarakat desa, maka pemerintah desa terjepit antara pemerintah di atasnya (camat, bupati, gubernur, presiden) dan masyarakat adat di bawahnya.
Oleh karena, kepala (pemerintah) desa menurut UU bertanggung jawab kepada bupati (via camat), dan tidak lagi pada masyarakat di bawahnya, maka dengan sendirinya kepala desa memihak pada pemerintah di atasnya dan mengusahakan agar masyarakat desa tunduk pada pemerintah atasan.
Dengan demikian kepala desa tidak lagi berfungsi sebagai pelindung masyarakat di desanya, tetapi dia terpaksa melindungi diri sendiri terhadap kekuasaan di atasnya yang menurut UU berwenang menentukan nasibnya sebagai aparat pemerintah yang paling rendah tingkatnya.
UU 5/1979 mengandung birokratisasi dan modernisasi, antara lain memperkenalkan satuan administratif, bernama kelurahan.
Desa di perkotaan yang sudah modern dapat diubah menjadi kelurahan. Menindaklanjuti UU No.5/1979 itu, Mendagri mengeluarkan Keputusan No.140-502 tahun 1979.
Isinya, menetapkan desa-desa di dalam kota diubah satusnya menjadi kelurahan.
Kota Surabaya, misalnya dibagi menjadi 38 lingkungan dan 103 desa.
Dalam peleburan menjadi kelurahan, 38 lingkungan diubah menjadi 60 kelurahan dan 103 desa menjadi 103 kelurahan, sehingga total di Kota Surabaya ada 163 kelurahan.
Kami hendak mengatakan bahwa munculnya keluarahan ini, yang dimulai tahun 1979 dan kemudian dari tahun ke tahun semakin bertambah, merupakan upaya pemerintah untuk merampas tanah desa, sekaligus pelan-pelan menghapuskan desa untuk diganti menjadi kelurahan.
Kalau pembangunan berhasil menciptakan kota maka dengan mudah menghapus desa dengan cara mengganti desa menjadi kelurahan.
Dari segi kepentingan pemerintah pusat, UU No. 5/1979 tentu membawa banyak manfaat. Penetrasi pemerintahan pusat pada daerah-daerah pedesaan di Indonesia pada umumnya, khususnya di desa-desa luar Jawa dan Madura, lebih sangat efektif.
Keseragaman struktur pemerintahan desa bagi seluruh desa juga menguntungkan pemerintah pusat karena keseragaman itu memudahkan pemerintah menjalankan pembinaan terhadap pemerintah desa.
Pelaksanaan program Inpres Bandes juga bisa berjalan secara efektif (menurut kacamata pemerintah) karena dijalankan dalam kerangka pemerintahan desa yang seragam.
Demikian juga dengan agenda konsolidasi politik (kebijakan massa mengambang) dan keamanan yang bekerja secara efektif dalam birokrasi sipil-militer yang paralel, seragam dan hirakhis.
Sebaliknya bagi masyarakat terutama masyarakat adat di luar Jawa dan Madura implementasi UU No.5/1979 tersebut menimbulkan dampak negatif yang tidak kecil.
Pemerintah daerah di Luar Jawa dipaksa berlawanan dengan masyarakat adat karena harus menghilangkan kesatuan masyarakat hukum (Rechtsgemeenschap) yang dianggap tidak menggunakan kata desa seperti Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang, Gampong di Aceh, Huta, Sosor dan lumban di Mandailing, Kuta di Karo, Binua di Kalimantan Barat, Negeri di Sulawesi Utara dan Maluku, Kampung di Kalimantan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan, yo di Sentani Irian Jaya, dan lain-lain.
Kesatuan masyarakat hukum yang telah dijadikan desa itu harus memiliki pemerintahan yang akan melaksanakan kewenangan, hak dan kewajiban desa serta menyelenggaraan pemerintahan desa, seperti ditetapkan dalam UU No.5/1979.
Kesatuan masyarakat hukum tidak hanya secara formal dan nomenklatur berganti nama menjadi desa, tetapi harus secara operasional segera memenuhi segala syarat yang ditentukan oleh UU No.5/1979.
Kebijakan UU No. 5/1979 tentu menuai badai protes dari berbagai pihak. Protes yang sangat keras muncul dari masyarakat, misalnya, di Sumatera Barat.
Mereka menyerukan bahwa UU No. 5/1979 sebagai bentuk Jawanisasi, penyeragaman yang tidak peka terhadap kondisi sosial-budaya setempat, dan menghancurkan identitas dan harga diri orang Minangkabau.
Karena itu pemaksaaan UU itu dan kerja-kerja Pemerintah Daerah berjalan sangat alot.
Pemerintah Daerah Sumbar sadar betul akan bahaya dan dampak negatif pelaksanaan UU No. 5/1979 itu. Tetapi pemerintah daerah toh tidak bisa mengelak dari perintah Jakarta.
Karena itu untuk menyesuaikan undang-undang tersebut dengan situasi sosial budaya masyarakat lokal Minangkabau, Pemda Sumbar melalui Perda No. 13/1983 membentuk apa yang dikenal dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN).
Anggota KAN ini terdiri dari pimpinan adat dan bertugas untuk memutuskan segala masalah adat yang timbul dalam nagari.
Walaupun nagari sebagai unit pemerintahan telah dihapus oleh UU No.5/1979, apa yang dilakukan oleh Pemda Sumbar merupakan suatu bukti bahwa ada masalah dalam keputusan pemerintah tentang penyeragaman struktur pemerintahan desa bagi seluruh Indonesia.
Meski begitu perlawanan ini dapat dikatakan tidak berarti. Karena perlawanan itu hanya sekadar memoles permasalahan yang sebenarnya, dan tidak menyentuh pokok permasalahan yang sebenarnya.
Dengan pergantian dari nagari, dusun, marga, gampong, huta, sosor, lumban, binua, lembang, kampung, paraingu, temukung dan yo menjadi desa berdasarkan UU No.5/1979 maka desa-desa hanya berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, dan tidak dinyatakan dapat “mengurus dan mengatur rumahtangganya sendiri”.
Dengan kata lain, desa tidak lagi otonom. Karena ia tidak lagi otonom, desa kemudian tidak lebih dari sekedar ranting patah yang dipaksakan tumbuh pada ladang pembangunan yang direncanakan rezim Orde Baru.
Secara substantif UU No. 5/1979 mengandung sentralisasi-negaranisasi dalam konteks hubungan desa dengan negara (supradesa), dan otoritarianisme-korporatis di dalam internal pemerintahan desa.
Desa bukanlah unit yang otonom seperti halnya daerah, tetapi hanya organisasi pemerintahan terendah yang dikendalikan negara (the local state government) melalui tangan camat.
Negara betul-betul masuk ke desa. Kepala desa bukanlah pemimpin masyarakat desa, melainkan sebagai kepanjangan tangan pemerintah supra desa, yang digunakan untuk mengendalikan penduduk dan tanah desa.
UU No. 5/1979 menegaskan bahwa kepala desa dipilih oleh rakyat melalui demokrasi langsung. Ketentuan pemilihan kepala desa secara langsung itu merupakan sebuah sisi demokrasi (elektoral) di aras desa.
Di saat presiden, gubernur dan bupati ditentukan secara oligarkis oleh parlemen, kepala desa justru dipilih secara langsung oleh rakyat.
Karena itu keistimewaan di aras desa ini sering disebut sebagai benteng demokrasi di level akar-rumput.
Tetapi secara empirik praktik pemilihan kepala desa tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak rakyat karena hampir tidak people choice sejak awal sampai pemilihan (voting). Pilkades selalu sarat dengan rekayasa dan kontrol pemerintah supradesa.
Dalam studinya di desa-desa di Pati, Franz Husken menunjukkan bahwa pilkades selalu diwarnai dengan intimidasi terhadap rakyat, manipulasi terhadap hasil, dan dikendalikan secara ketat oleh negara.
Bagi Husken, pilkades yang paling menonjol adalah sebuah proses politik untuk penyelesaian hubungan kekuasaan lokal, ketimbang sebagai arena kedaulatan rakyat.mengelak dari perintah Jakarta.
Cacat demokrasi desa tidak hanya terlihat dari sisi pilkades, tetapi juga pada posisi kepala desa. UU No. 5/1979 menobatkan kepala desa sebagai “penguasa tunggal” di desa.
Desa dibuat sebagai “negara kecil”, yang berarti dia diposisikan sebagai wilayah, organ dan instrumen kepanjangan tangan negara yang memang tersusun secara hirarkhis-korporatis, bukan sebagai tempat bagi warga untuk membangun komunitas bersama.
Desa bukanlah local-self government melainkan sekadar sebagai local-state government. Kepala desa adalah kepanjangan tangan birokrasi negara yang menjalankan perintah untuk mengendalikan wilayah dan penduduk desa.
Karena itu Hans Antlov menyebutnya sebagai negara masuk desa. Kepala desa mengendalikan seluruh hajat hidup orang banyak, dia harus menhetahui apa saja yang terjadi di desa, termasuk selembar daun yang jatuh dari pohon di wilayah yurisdiksinya.
Ken Young bahkan lebih suka menyebut kepala desa sebagai “fungsionaris negara” ketimbang sebagai “perangkat desa”, karena dia lebih banyak menjalankan tugas negara ketimbang sebagai pemimpin masyarakat desa.
UU No. 5/1979 sebenarnya juga mengenal pembagian kekuasaan di desa, yakni ada kepala desa dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD).
Pasal 3 menegaskan, pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan Lembaga Musyawarah Desa (LMD).
Lembaga Musyawarah Desa adalah lembaga permusyawaratan atau pemufakatan yang keanggotaannya terdiri atas Kepala-kepala Dusun , Pimpinan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, dan pemuka-pemuka masyarakat di esa yang bersangkutan (Pasal 17).
Meski ada pembagian kekuasaan, tetapi LMD tidak mempunyai kekuasaan legislatif yang berarti.
LMD bukanlah wadah representasi dan arena check and balances terhadap kepala desa. Bahkan juga ditegaskan bahwa kepala desa karena jabatannya (ex officio) menjadi ketua LMD (Pasal 17 ayat 2).
Jika di desa kepala desa menjadi penguasa tunggal, tetapi kalau dihadapan supradesa, kepala desa hanya sekadar kepanjangan tangan yang harus tunduk dan bertanggungjawab kepada supradesa.
Menurut UU No. 5/1979 Kepala Desa diangkat dan diberhentikan oleh Bupati /Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I (pasal 6 dan 9), untuk masa jabatan selama 8 tahun, dan dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan berikutnya (pasal 7).
Kepala Desa menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pimpinan pemerintahan desa yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggung jawab utama dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah desa, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan desa.
Dalam menjalankan hak, wewenang, dan kewajiban pimpinan pemerintah desa, Kepala Desa bertanggung jawab kepada pejabat yang berwenang mengangkat melalui Camat; dan memberikan keterangan pertanggungjawaban tersebut kepada Lembaga Musyawarah Desa (Pasal 10).
Sebagian besar kepala desa bukanlah pemimpin masyarakat yang berakar dan legitimate di mata masyarakat meski secara fisik dekat dengan rakyat, melainkan menjadi bagian dari birokrasi negara yang mempunyai segudang tugas kenegaraan: menjalankan birokratisasi di level desa, melaksanakan program-program pembangunan, memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat, serta melakukan kontrol dan mobilisasi warga desa. Jika pemerintah desa menjadi sentrum kekuasaan politik, maka kepala desa merupakan personifikasi pemerintah desa.
Banyak pihak telah menyampaikan kritik bahwa modernisasi desa itu merupakan bentuk pemaksaan (imposition)–sebuah intervensi negara yang paling ekstrem–dari atas secara gegabah, yang menghancurkan tatanan kehidupan lokal.
Dalam praktik, di satu sisi, proyek modernisasi yang intervensionis itu tidak membuahkan hasil yang gemilang.
Di sisi lain, masyarakat lokal mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan pemerintahan desa yang dibuat pemerintah.
Akibatnya desa-desa genealogis bersifat dualistik: mempunyai struktur baru pemerintahan desa dan masih tetap menjalankan tradisi dan struktur lama.
Struktur baru pemerintahan desa bekerja apa adanya, tidak mampu menjalankan tiga fungsi utama secara memadai, kurang bermanfaat bagi masyarakat setempat, kecuali hanya melayani dan menjalankan tugas-tugas administratif dan politik dari atas.
Karena itu wajar jika di masa lalu, jabatan kepala desa dan perangkat desa tidak diminati masyarakat, apalagi bagi generasi muda yang berpendidikan tinggi.
UU No. 5/1979 digantikan oleh UU No. 22/1999 yang lebih liberal, mempunyai spirit otonomi dan demokrasi desa. Meskipun sudah diganti, tetapi watak pemerintahan birokratik dan desa korporatis warisan Orde Baru, masih sangat kuat di era reformasi.
Secara normatif UU No. 22/1999 mendefinisikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten, menempatkan desa tidak lagi sebagai bentuk pemerintahan terendah di bawah camat, melainkan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan hak asal-usul desa.
Implikasinya adalah, desa berhak membuat regulasi desa sendiri untuk mengelola barang-barang publik dan kehidupan desa, sejauh belum diatur oleh kabupaten.
Dalam Pasal 105, misalnya, ditegaskan: “Badan Perwakilan Desa bersama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa”.
Ini artinya, bahwa desa mempunyai kewenangan devolutif (membuat peraturan desa) sekaligus mempunyai kekuasaan legislatif untuk membuat peraturan desa itu.
Lompatan lain yang tampak dalam UU No. 22/1999 adalah pelembagaan demokrasi desa dengan lahirnya Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai pengganti Lembaga Musyawarah Desa (LMD). Pasal 94 UU No. 22/1999 menegaskan:
“Di Desa dibentuk Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa, yang merupakan Pemerintahan Desa”.
Sedangkan Pasal 104 menegaskan: Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
BPD menjadi arena baru bagi kekuasaan, representasi dan demokrasi desa. BPD dilahirkan sebagai bentuk kritik terhadap LMD. Pembentukan BPD melibatkan secara terbatas partisipasi masyarakat.
Ia menjadi sebuah arena demokrasi perwakilan yang lebih baik ketimbang LMD. Berbeda dengan LMD masa lalu yang ditunjuk oleh lurah, BPD sekarang dipilih dengan melibatkan masyarakat. Jika dulu LMD merupakan lembaga korporatis yang diketuai secara ex officio dan didominasi oleh kepala desa, sekarang kepala desa ditempatkan sebagai eksekutif sementara BPD sebagai badan legislatif yang terpisah dari kepala desa.
Dengan kalimat lain, lahirnya BPD telah membawa pergeseran kekuasaan yang lebih jelas antara kepala desa sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan BPD sebagai pemangku lembaga legislatif. Paling tidak ada tiga domain kekuasaan kepala desa yang telah dibagi ke BPD:
(1) pembuatan keputusan dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes) yang dikerjakan bersama-sama antara lurah dan BPD;
(2) pengelolaan keuangan yang melibatkan BPD seperti penyusunan APBDES dan pelelangan tanah kas desa;
(3) rekrutmen perangkat desa yang dulu dikendalikan oleh lurah dan orang-orang kecamatan maupun kabupaten sekarang dikendalikan oleh BPD. Bahkan kontrol BPD terhadap kepala desa sudah dijalankan meski kontrol itu masih terbatas pada LPJ lurah dan ia belum terinstitusionalisasi kepada masyarakat.
Sumbangan BPD terhadap demokrasi desa memang sangat beragam. Ada yang positif ada pula yang negatif. Kehadiran BPD jelas membuka ruang kontrol dan keseimbangan kekuasaan di desa.
Bagi lurah yang mempunyai sense of legitimacy merasa lebih ringan menanggung beban psikopolitik dalam membuat keputusan, setelah ditopang partnership dengan BPD.
Sebab keputusan desa yang dulu dimonopoli oleh lurah, sekarang bisa dibagi kepada BPD yang memungkinkan tekanan-tekanan publik kepada lurah semakin berkurang, dan dengan sendirinya akan beralih juga kepada BPD.
Di banyak desa, yang paling menyolok, kehadiran BPD telah membuat “hati-hati” lurah dalam bertinndak, sehingga sekarang banyak lurah yang bekerja lebih transparan dan bertanggungjawab.
Namun, di banyak tempat, hadirnya BPD tidak memberikan sumbangan bagi pelembagaan demokrasi desa secara matang, dewasa dan santun, melainkan menjadi sumber masalah baru karena peran lembaga perwakilan itu yang “kebablasan” dan menimbulkan pertikaian dengan pemerintah desa.
Banyak kepala desa yang melaporkan (wadul) bahwa dirinya digencet oleh “Badan Provokasi Desa”.
Di sebuah desa, misalnya, selepas lurah desa mengundurkan diri karena bermasalah, tidak ada warga yang sanggup mencalonkan diri sebagai kepala desa karena trauma yang mendalam kepada sepak terjang BPD.
Di sisi lain, di mata kades, BPD sering melanggar batas-batas kekuasaan dan kewenangan yang telah digariskan dalam regulasi.
Sekarang lurah menghadapi tekanan dan instruksi dari atas (kabupaten), gencetan dari samping (Badan Perwakilan Desa, BPD) dan tuntutan dari masyarakat.
Tetapi hubungan konfliktual antara pemerintah desa dan BPD itu lambat laun mulai mencair, setidaknya mulai tahun ketiga.
Di banyak desa, hubungan antara pemerintah desa dan BPD mulai terbangun trust dan kemitraan yang lebih baik.
BPD juga belum mampu mengayuh di antara dua karang: negara dan masyarakat. Eksistensi, sepak terjang, dan keputusan BPD (sebagai oligarki) elite lebih banyak berkiblat pada negara ketimbang berbasis pada masyarakat. Lahirnya BPD di empat desa sendiri diikat oleh Perda.
Perda beserta juklak dan juknisnya merupakan referensi utama bagi BPD dalam membuat keputusan. Artinya BPD membuat Perdes hanya sebagai sebuah respons terhadap Perda yang dibuat oleh kabupaten.
Tampaknya belum ada pemikiran BPD untuk melibatkan masyarakat secara partisipatif (atau setidaknya konsultasi publik) dalam proses pembuatan keputusan. Yang populer dalam benak mereka adalah sosialisasi Raperdes.
Raperdes yang disusun oleh BPD bersama kades, sebagai bentuk respons terhadap Perda, umumnya “disosialisasikan” kepada masyarakat, khususnya para ketua RT dan tokoh masyarakat.
Namun sosialisasi Raperdes itu cenderung bias elite, tidak membuka perdebatan wacana secara luas, dan tidak melibatkan masyarakat luas dalam agenda setting secara bersama-sama.
Perda, yang selalu menjadi rujukan BPD dan pemerintah desa, sudah dilengkapi dengan rambu-rambu, juklak, dan juknis sebagai pedoman yang harus “ditaati” oleh desa.
Jika pemerintah desa dan BPD membuat Perdes secara menyimpang dari Perda, meski berbasis pada masyarakat, maka kabupaten bisa menggunakan hak vetonya menggagalkan Perdes.
Dengan demikian, otonomi desa yang berbasis pada partisipasi masyarakat masih sangat lemah, dan hal itu tidak dimainkan dengan baik oleh BPD.
Meski menciptakan lompatan yang luar bisa, tetapi UU No. 22/1999 tetap memiliki sejumlah keterbatasan, terutama kalau dilihat dari sisi desain desentralisasi.
Setelah mencermati wacana yang berkembang di Departemen Dalam Negeri, kami memperoleh informasi bahwa pemerintah hendak menyerahkan sepenuhnya persoalan desa kepada kabupaten/kota.
Kehendak inilah yang membuat rumusan UU No. 22/1999 memberikan “cek kosong” pengaturan desa kepada kabupaten/kota. UU No. 22/199 hanya memberikan diktum yang sifatnya makro dan abstrak dalam hal desentralisasi kewenangan kepada desa.
Di satu sisi ini adalah gagasan subsidiarity yang baik, tetapi kami menilai bahwa pemerintah tampaknya tidak mempunyai konsepsi yang memadai (jika tidak bisa disebut kurang mempunyai komitmen serius) untuk merumuskan disain desentralisasi dan otonomi desa.
Sebagaimana ditunjukkan oleh Selo Sumardjan (1992), pemerintah sebenarnya mengalami kesulitan dalam mengatur otonomi desa, sejak awal kemerdekan, khususnya sejak 1965.
Jika dilihat dari sisi hukum ketetanegaraan, pemberian cek kosong kepada kabupaten sangat tidak tepat, sebab yang melakukan desentralisasi adalah negara, bukan kabupaten/kota.
UU No. 22/1999 membuat kabur (tidak jelas) posisi desa karena mencampuradukkan antara prinsip self-governing community (otonomi asli) dan local-self government (desentralisasi) tanpa batas-batas perbedaan yang jelas.
Pengakuan desa sebagai self-governing community (otonomi asli) lebih bersifat simbolik dan nostalgia, ketimbang substantif. Setelah UU No. 22/199 dijalankan, tidak serta-merta diikuti dengan pemulihan otonomi asli desa, terutama otonomi dalam mengelola hak ulayat desa adat.
Menurut UU No. 22/1999, kewenangan Desa mencakup:
(1) kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa;
(2) kewenangan yang oleh peraturan perundang-perundangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah; dan
(3) Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten.
Ayat (1) menunjukkan bahwa desa memiliki kewenangan asli yang tidak boleh diintervensi oleh pemerintah supradesa.
Namun hal ini dalam kenyataannya tidak jelas kewenangan yang dimaksud, sehingga desa tetap saja tidak mempunyai kewenangan yang benar-benar berarti (signifikan) yang dapat dilaksanakan secara mandiri (otonom).
Kewenangan yang selama ini benar-benar dapat dilaksanakan di desa hanyalah kewenangan yang tidak mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat desa itu sendiri.
Kewenangan asli tersebut sebenarnya yang menjadi pertanda bagi desa sebagai kesatuan masyarakat hukum atau desa sebagai subyek hukum yang otonom.
Tetapi, sekarang, kewenangan generik bukan hanya susah untuk diingat kembali, tetapi sebagian besar sudah hancur.
Komunitas adat (desa adat) yang paling menderita atas kehancuran kewenangan generik. Adat telah kehilangan eksistensinya sebagai subyek hukum untuk mengelola property right.
Banyak tanah ulayat yang kemudian diklaim menjadi milik negara. Ketika desa dan adat diintegrasikan ke dalam negara, maka negara membuat hukum positif yang berlaku secara nasional, sekaligus meniadakan hukum adat lokal yang dulunya digunakan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
Sengketa hukum dan agragia antara negara dengan adat pun pecah dimana-mana yang sampai sekarang sulit diselesaikan secara karitatif karena posisi (kedudukan) desa adat yang belum diakui sebagai subyek hukum yang otonom
Di tingkat lokal juga sering terjadi dualisme antara kepala desa dengan penghulu adat atau sering terjadi benturan antara “desa negara” dengan “desa adat” yang menggelar sengketa dalam hal pemerintahan, kepemimpinan, aturan dan batas-batas wilayah.
Titik krusial lain adalah perubahan dari kewenangan mengatur dan mengurus “rumah tangga sendiri” menjadi kewenangan mengatur dan mengurus “kepentingan masyarakat setempat” sebagaimana terumuskan dalam UU No. 22/1999.
Kalau hanya sekadar kewenangan mengelola “kepentingan masyarakat setempat”, kenapa harus diformalkan dalam UU, sebab selama ini masyarakat sudah mengelola kepentingan hidup sehari-hari mereka secara mandiri.
Tanpa pemerintah dan UU sekalipun masyarakat akan mengelola kepentingan mereka sendiri. Dimata para kepala desa, mengurus dan melayani kepentingan masyarakat setempat sudah merupakan kewajiban dan tanggungjawab mereka sehari-hari.
Ayat (2) menunjukkan betapa desa hanya akan memperoleh kewenangan sisa dari kewenangan pemerintah supradesa (otonomi residu).
Sementara pada ayat (3) sebenarnya bukanlah termasuk kategori kewenangan desa karena tugas pembantuan hanyalah sekedar melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.
Dengan demikian makna tugas pembantuan bukanlah merupakan kewenangan desa tetapi sekedar sebagai pelaksana dari sebuah kegiatan yang berasal dari pemerintah supradesa.
Sebagai turunan dari UU No 22/99, terdapat aturan yang mencakup kewenangan desa, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 76/2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa. PP ini menegaskan sejumlah kewenangan desa, yaitu:
- Penetapan bentuk dan susunan organisasi pemerintahan desa; Pencalonan, pemilihan dan penetapan Kepala Desa
- Pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan penetapan perangkat desa
- Pembentukan dan penetapan lembaga masyarakat
- Penetapan dan pembentukan BPD
- Pencalonan, pemilihan dan penetapan angota BPD
- Penyusunan dan penetapan APBDes; Pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat
- Penetapan peraturan desa
- Penetapan kerja sama antar desa
- Penetapan dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)
- Pengeluaran ijin skala desa
- Penetapan tanah kas desa
- Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat
- Pengelolaan tugas pembantuan
- Pengelolaan atas dana bagi hasil perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten dan kota.
Penetapan dan pembentukan BPD sebenarnya juga belum diserahkan sepenuhnya kepada desa.
Hal ini ditunjukkan dengan adanya Perda yang masih mengatur dan membatasi jumlah anggota BPD.
Karena akhirnya yang memberi honor kepada anggota BPD adalah desa itu sendiri, maka sebenarnya tidak perlu ada pembatasan jumlah anggota BPD, yang lebih penting adalah tingkat representasi dari anggota BPD itu sendiri.
Bila suatu desa menghendaki jumlah anggota BPD lebih besar, hal itu tidak perlu dilarang karena risiko penambahan anggota dengan tambahan beban honor bagi anggota BPD akan ditanggung oleh desa itu sendiri.
Di sisi lain kewenangan desa untuk menetapkan peraturan desa, kadang-kadang justru menimbulkan beban bagi masyarakat terutama peraturan yang menyangkut pungutan-pungutan.
Pengelolaan tugas pembantuan sebenarnya juga bukan kewenangan desa, melainkan tugas (beban) yang diberikan kepada desa.
Titik kewenangannya justru bersifat “negatif”, yaitu kewenangan desa menolak tugas pembantuan bila tidak disertai pendukungnya.
Meskipun ada banyak kelemahan, sejak 2000, UU memunculkan semangat dan gerakan baru otonomi desa.
Di banyak daerah muncul asosiasi desa yang melakukan advokasi terhadap kebijakan kabupaten, menunut alokasi dana desa, menolak kebijakan yang merugikan desa.
Kelak asosiasi ini terus memperjuangkan otonomi desa, termasuk memperjuangkan kelahiran UU Desa.
Di daerah ada juga gerakan kembali ke akar, dan yang lebih menarik adalah munculnya kebijakan alokasi dana desa yang dimulai oleh Kabupaten Solok tahun 2001, kemudian disusul oleh kabupaten lain di penjuru Indonesia.
Pengalaman inilah yang kemudian memberi ilham bagi revisi UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan perimbangan keuangan menjadi sumber penerimaan desa dalam UU 32/2004, yang diterjemahkan secara eksplisit sebagai aloksasi dana desa dalam PP No. 72/2005.
UU No. 32/2004 beserta turunannya kian melemahkan demokrasi desa, tetapi melakukan inovasi pada sisi perencanaan dan sumber keuangan desa berupa ADD.
Dua isu ini ditangkap para pegiat desa untuk menggerakkan otonomi desa, sambil memberikan advokasi pada RUU Desa, yang dimulai pada tahun 2007.
Perencanaan desa tersebut memberikan manfaat secara sosial, politik dan ekonomi kepada desa.
Secara sosial, proses perencanaan desa yang bersifat partisipatoris-kolektif menjadi arena untuk memperkuat kohesi sosial dan menyemai mutual trust antara pemerintah desa, lembaga-lembaga desa, organisasi masyarakat dan warga.
Secara politik, perencanaan desa memberikan banyak manfaat:
(a) Sebagai instrumen untuk membangun kepemimpinan lokal yang demokratis dan visioner;
(b) menjadi arena bagi democratic engagement, membuka akses partisipasi bagi kaum marginal dan perempuan, sehingga mampu menembus struktur politik yang aristokratis, patriarkhis dan otokratis;
(c) menjadi arena pembuatan keputusan desa secara kolektif dan mandiri sebagaimana ditunjukkan dengan emansipasi dalam pelayanan publik dan pengembangan ekonomi lokal;
(d) RPJMDes merupakan instrumen politik representasi dan negosiasi desa di hadapan pihak luar dan pemerintah supradesa.
Secara ekonomi, perencanaan desa menjadi arena dan instrumen untuk mengidentifikasi aset-aset ekonomi lokal yang kemudian diputuskan dalam Musrenbang, dan dijalankan secara kolektif oleh pemerintah desa dan warga masyarakat.
Di sisi lain dengan semangat “satu desa satu rencana”, desa melakukan integrasi antara perencanaan reguler dengan perencanaan PNPM Mandiri dalam satu proses dan satu dokumen.
Namun demikian, anggaran PNPM maupun anggaran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) lainnya masih berdiri sendiri.
Para pihak berharap dan merekomendasikan agar RUU Desa melembagakan “satu desa, satu rencana dan satu anggaran”. Berbagai kewenangan/urusan menjadi basis perencanaan desa.
Lalu kewenangan dan perencanaan ini didukung dengan APBDes yang salah satu sumbernya adalah Dana Alokasi Desa. Berbagai BLM lebih baik dikonsolidasikan menjadi satu DAD.
(Artikel ini dikutip dari buku “Kembali ke Mandat: Hasil Pengawasan Komite I DPD RI Atas Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”. Kami melakukan penyuntingan ulang dan menerbitkannya kembali untuk rubrik Opini)
Dalam rangka lima tahun terbitnya UU Desa pada 15 Januari 2014, kami menayangkan 8 artikel opini mengenai UU Desa. Diantaranya:
- UU Desa: Amanat Reformasi dan Desa yang Beragam
- Debat Ideologi dan Perspektif tentang Desa
- Negara yang Mengubah, Merusak dan Menindas Desa
- UU Desa: Lima Perubahan Pokok dan Tantangan Pelaksanaan ke Depan
- Kontradiksi Kelembagaan dalam UU Desa
- Jungkir Balik Regulasi Pelaksanaan UU Desa
- Agenda-agenda yang Terabaikan dalam UU Desa
- Mendampingi Desa Menjadi Subyek Perubahan